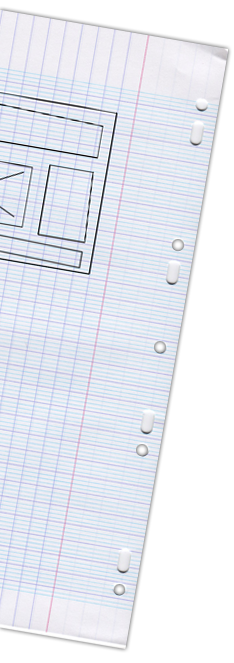Perempuan
Kenangan
Oleh :
Farihatun Nafiah
Deru
pesawat. Ia menelisik gumpal awan. Menerabas begitu saja. Hilang atau entah.
Pikiranku terlempar pada satu demi satu ingatan. Dadaku tertegun, namun mataku
tetap terpejam.
Rambut
kecokelatan yang terurai. Kita harus tetap tersenyum dan menjadi diri sendiri,
katamu. Kelingking saling bertaut. Waktu itu, umur sembilan tahun. Aku tidak
lagi merasa sendiri. Tak lama kemudian, kau juga aku, melesat di sebuah hamparan.
Tawa lepas. Angin yang menerbangkan serpihan-serpihan dandelion. Kita
berlari-lari hingga lelah. Lejar.
“Allita,
ayo kembali!” Aku berteriak sementara keringat mulai melata di dahi.
“Pulanglah
dulu!” Kau memunggungiku.
Aku
tahu, kau sedang butuh sendiri. Lantas kau memunguti rerumput lalu merangkainya
menjadi mahkota. Bagiku, kau satu-satunya gadis kecil yang dapat membilai
lubang sebuah derita; perceraian dua orang yang tersayang. Sebenarnya, kita
sama-sama terlampau pagi untuk menelan apa yang
terjadi.
“Besok
aku berangkat. Aku akan tinggal bersama ayah. Naik pesawat.” Kau menoleh dengan
senyum semarai.
Kucoba
untuk mendekat. “Allita, mainlah ke rumahku terlebih dahulu, ambil bunga-bunga
matahari di halaman. Kau boleh memetik semua, jika kau mau,” lalu mulutku
terasa beku.
Kau
menatapku tanpa berucap. Kulihat sepasang mata bening, ada titik kesedihan
disana. Aku merasai akan ada yang sangat jauh.
***
Kau
tetap sahabat terbaikku, katamu melalui surat pada pertengahan tahun 1998. Ketika
itu aku sangat gembira, rasanya, dikenang itu sungguh menyenangkan. Terlebih itu
dirimu, Allita. Aku menulis berlampir-lampir surat balasan, namun gagal
kukirim. Bukan apa-apa. Aku memang tidak sanggup.
Masihkah
ada bunga-bunga matahari di rumahmu, isi suratmu yang kedua, aku melingkari
kalimat itu dengan tinta warna merah muda—warna baju kesukaanmu. Masih Allita,
aku selalu merawatnya lantas kau kapan kemari. Penaku tiba-tiba terhenti,
harapan itu terlalu berat. Aku membalas suratmu namun lagi-lagi tidak mengirimkannya.
Datanglah
ke acara resepsiku minggu depan, semoga kau sempat. Surat ketiga, pada penghujung
tahun 2000. Aku ingin berbisik, Allita, disini tiba-tiba musim gugur dan aku harus
menikmatinya. Membayangkan apa yang harus kulakukan bilamana hadir di pestamu.
Bersalaman? Memeluk? Menangis? Tertawa? Mengatakan hal-hal manis untuk
pernikahan itu? Ah, betapa konyol. Kupandangi lagi suratmu itu sementara
berbotol-botol bir telah tandas.
Aku
tertekan hidup bersama Jef, aku terlalu payah untuk terus berpura-pura tidak
terjadi apapun di hadapan ayah. Itu isi suratmu yang kesekian. Tanganku
bergetar menuliskan secarik balasan, isinya semoga kau baik-baik disana dan
hubungan rumah tanggamu segera harmonis kembali. Surat itu kulipat dengan pedih
yang rapi. Kuberi tanda sehelai kering kelopak bunga matahari. Kumasukkan dalam
amplop, warnanya kekuningan yang teramat lesi. Kutempeli perangko dengan gambar
gadis yang rambutnya terurai. Lalu kutitipkan pada angin yang menimpali. Kau tahu,
saat itu memang sedang musim angin, musim yang membawa suratmu terbang bersama kapuk-kapuk
randu yang saling mengerumuni.
Allita,
kau mengembalikan satu kenangan. Kau benar, menjadi ayah adalah sesuatu yang
tak mudah dan seorang ayah memang tidak patut untuk kecewa. Ayahku—mungkin
sejak kecil—pecinta bunga matahari. Ibu pernah menggerutui ayah sebab ulat-ulat
bulu merambati tiap sudut rumah. Berhari-hari seperti ada gemuruh yang terus
berkecamuk dalam diam.
“Kau
tahu, serotonin di dalam kuaci mampu membuat hari minggu kita menjadi
benar-benar relaks!” ayah tertawa kecil seraya meletakkan kulit biji kecil itu
di atas lapik cawan.
Aku
hanya memanggut-manggut menikmati kuaci, ayah memang pembaca yang baik.
Sementara tawa ibu berderai begitu saja, dengan perlahan kami sama-sama mengisap
teh aroma melati yang mulai hangat. Kepalaku masih menyimpan harum dedaun juga suasana
cair di teras. Namun tak mungkin lagi kudapati hari semanis itu.
“Anakku!
Istriku! Cepat lari cepat! Aaaaaaarghh!!”
Suara berat yang melemah. Luka menganga pada dada juga perutnya. Lenyah.
Aku membatu
dengan bercak yang mungkin akan terus basah, seperti luber lantai kami. Merah
kental. Orang-orang ramai. Sementara kulihat ibu benar-benar lari bersama
seseorang yang telah membuat ayahku sekarat, lalu mati.
Aku tetap
mematung di tepian jendela. Patung yang terus menanti kedatangan ibu dan
merindukan wujud ayah. Sampai satu hari, ada noktah yang mengisi pandangan
kosongku. Aku berkedip. Ada bocah perempuan yang mengintipku dari sela-sela
pagar. Tangannya berusaha menggapai sesuatu.
“Petiklah!
Tidak apa-apa,” kataku dengan membilas mata yang berembun.
“Terimakasih!
Kutunggu kau di hamparan dandelion, besok!” Ah, Allita.
***
“Bas,
aku menunggumu nanti malam, di tempat biasa, kamar nomor 56.” Sebuah pesan
singkat dari seseorang. Kau dulu kerap menangis gara-gara bunga mataharimu
direbut olehnya, Allita. Tentu kau ingat, dia Roy. Sejak sebelas tahun yang
lalu—sebelum akhirnya tiada, dia yang menemaniku agar tidak lagi merasa
sendiri. Aku bahagia menjadi diri sendiri, bersamanya.
“Bas…,”
ah, seperti suara perempuan. Mataku benar-benar terpejam. Ingin kubuka. Tetapi
berat sekali. Sungguh. (*)
Jombang,
5 September 2015